Kalau sebuah sistem ekonomi hanya menciptakan ketimpangan, yang membiarkan 1% elit merampas masa depan 99% rakyat, apakah itu bisa dianggap sejalan dengan cita-cita demokrasi? Tidak. Sebab, kalau ada segelintir orang yang begitu berkuasa, sehingga bisa membeli segala-galanya dengan kekayaannya, maka institusi demokrasi pun akan kedodoran.
Fenomena itu sangat nyata di Indonesia. Di satu sisi, Indonesia dipuja-puji sebagai kampiun demokrasi. Apa yang disebut “proses demokratisasi” di Indonesia selalu menjadi rujukan bagi negara-negara yang baru keluar dari otoritarianisme. Bahkan, Indonesia digelari negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.
Namun, pada sisi lainnya, penerapan neoliberalisme, yang berjalan pararel dengan “proses demokratisasi” tersebut, telah menghasilkan ketimpangan ekonomi yang sangat luar biasa. Data Biro Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, tingkat kesenjangan ekonomi pada 2011 menjadi 0,41. Padahal, pada tahun 2005, gini rasio Indonesia masih 0,33. Bahkan, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto pernah membeberkan bahwa hanya 0,2 persen penduduk Indonesia yang saat ini menguasai 56 persen aset nasional.
Kenapa bisa begitu? Boleh jadi apa yang kita maksud sebagai “proses demokrasi” adalah bukan demokrasi atau pseudo-demokrasi. Artinya, demokrasi liberal yang sementara ini kita anut bukanlah sebuah demokrasi yang sebenarnya. Melainkan, seperti dikatakan oleh Naomi Klein, hanya sebuah permainan untuk menipu kita bahwa seolah-olah perampokan elit terhadap rakyat itu sah-sah saja dan masih sesuai dengan aturan main.
Ada beberapa fakta menunjukkan betapa sistem neoliberalisme memang tidak sejalah dengan sistem demokrasi.
Pertama, fakta historis menunjukkan bahwa praktek pertama neoliberalisme di dunia justru dilakukan di bawah kediktatoran. Dua penggagas utama ide neoliberalisme, Friedrich Von Hayek dan Milton Friedman, kebingunan mencari negara untuk mempraksiskan ajaran-ajarannya. Tidak ada satupun negara yang dikategorikan demokratis mau menjalankan anjuran dua professor itu. Akhirnya, pada tahun 1970-an, mereka mulai melirik diktator militer di Chile dan Turki.
Dengan demikian, proyek pertama neoliberalisme di dunia justru dilakukan di bawah alam kediktatoran. Tak heran, Naomi Klein bilang, neoliberalisme tidak ada hubungannya dengan segala hal yang berbau demokrasi.
Di Eropa Barat, Margaret Tatcher juga memperkenalkan neoliberalisme setelah membatasi ruang demokrasi, mengobarkan perang di kepulauan Falkland, dan menghancurkan serikat buruh. Kita tahu, penghancuran serikat buruh di Inggris disertai dengan represi brutal dan sangat kejam.
Kedua, proses penerapan neoliberalisme terhadap negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia, adalah melalui cara-cara licik: jebakan utang. John Perkins, penulis buku Confessions of An Economic Hit Man, menceritakan bagaimana utang untuk mencekik leher negara penerima pinjaman. Setelah negara penerima pinjaman ini bertekuk lutut, negara kreditur pun dengan leluasa memaksakan kebijakan yang dikehendakinya.
Kita juga masih ingat, pada tahun 1997, ketika Indonesia terperosok dalam krisis ekonomi, IMF datang menawarkan pinjaman. Dalam waktu singkat Indonesia masuk dalam jebakan IMF. Sejak itu, Indonesia pun dipaksa menjalankan resep-resep neoliberal yang dikehendaki IMF. Dan, kita tahu, semua kebijakan IMF itu membawa malapetaka bagi rakyat Indonesia.
Ketiga, neoliberalisme ditandai oleh supremasi pasar dan korporasi terhadap negara dan, dengan demikian, rakyat. Dalam kondisi seperti ini, negara hanya difungsikan sebagai alat untuk memfasilitasi proses akumulasi keuntungan bagi segelitir elit/korporasi. Sedangkan suara rakyat, yang biasanya diminta setiap lima tahun sekali, tak lebih sebagai legitimator untuk berjalannya administrasi neoliberal.
Ini juga terjadi dalam kasus Indonesia. Sejak neoliberalisme dipraktekkan, partisipasi rakyat dalam politik merosot tajam. Bahkan, neoliberalisme sangat aktif mendepolitisasi massa-rakyat. Akibatnya, sekalipun ada proses pemilu reguler setiap lima tahun, tetapi proses pengambilan keputusan secara real telah berpusat di tangan segelintir elit.
Hasil survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menemukan, hanya 12,8 persen rakyat Indonesia yang mengaku bisa mempengaruhi pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan. Sebaliknya, mayoritas rakyat merasa sudah dikesampingkan dalam proses pengambilan kebijakan. Belum lagi, upaya rakyat untuk mempengaruhi kebijakan, misalkan dengan aksi protes, seringkali berhadapan dengan represi brutal.
Keempat, ketergantungan rezim nasional terhadap kekuatan kapital global telah mendorong transfer kekuasaan politik ke tangan kapital finansial. Akibatnya, para bankir, spekulan, investor, dan lembaga keuangan semakin punya kekusaan yang tak terbatas. Lembaga keuangan dan perdagangan internasional, seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO, telah mengambil peran dominan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi dan politik di Indonesia. Bahkan, kekuasaan mereka bisa melampaui kekuasaan DPR. Faktanya: hampir semua proses penyusunan UU di DPR tidak terlepas dari arahan lembaga-lembaga tersebut. Politisi PDIP Eva Sundari pernah mengungkapkan keberadaan 76 UU yang draftnya disusun oleh pihak asing. Artinya, proses penyusunan kebijakan di Indonesia, termasuk UU, tidak lagi mengacu pada konstitusi (UUD 1945) dan kehendak rakyat.
Dengan demikian, ada korelasi antara meningkatnya ketimpangan ekonomi dan semakin tersingkirnya rakyat dalam proses menentukan arah kebijakan pembangunan sebuah negara. Dan, di bawah sistem neoliberalisme, partisipasi rakyat dalam politik makin terdegradasi.
Fenomena itu sangat nyata di Indonesia. Di satu sisi, Indonesia dipuja-puji sebagai kampiun demokrasi. Apa yang disebut “proses demokratisasi” di Indonesia selalu menjadi rujukan bagi negara-negara yang baru keluar dari otoritarianisme. Bahkan, Indonesia digelari negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.
Namun, pada sisi lainnya, penerapan neoliberalisme, yang berjalan pararel dengan “proses demokratisasi” tersebut, telah menghasilkan ketimpangan ekonomi yang sangat luar biasa. Data Biro Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, tingkat kesenjangan ekonomi pada 2011 menjadi 0,41. Padahal, pada tahun 2005, gini rasio Indonesia masih 0,33. Bahkan, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto pernah membeberkan bahwa hanya 0,2 persen penduduk Indonesia yang saat ini menguasai 56 persen aset nasional.
Kenapa bisa begitu? Boleh jadi apa yang kita maksud sebagai “proses demokrasi” adalah bukan demokrasi atau pseudo-demokrasi. Artinya, demokrasi liberal yang sementara ini kita anut bukanlah sebuah demokrasi yang sebenarnya. Melainkan, seperti dikatakan oleh Naomi Klein, hanya sebuah permainan untuk menipu kita bahwa seolah-olah perampokan elit terhadap rakyat itu sah-sah saja dan masih sesuai dengan aturan main.
Ada beberapa fakta menunjukkan betapa sistem neoliberalisme memang tidak sejalah dengan sistem demokrasi.
Pertama, fakta historis menunjukkan bahwa praktek pertama neoliberalisme di dunia justru dilakukan di bawah kediktatoran. Dua penggagas utama ide neoliberalisme, Friedrich Von Hayek dan Milton Friedman, kebingunan mencari negara untuk mempraksiskan ajaran-ajarannya. Tidak ada satupun negara yang dikategorikan demokratis mau menjalankan anjuran dua professor itu. Akhirnya, pada tahun 1970-an, mereka mulai melirik diktator militer di Chile dan Turki.
Dengan demikian, proyek pertama neoliberalisme di dunia justru dilakukan di bawah alam kediktatoran. Tak heran, Naomi Klein bilang, neoliberalisme tidak ada hubungannya dengan segala hal yang berbau demokrasi.
Di Eropa Barat, Margaret Tatcher juga memperkenalkan neoliberalisme setelah membatasi ruang demokrasi, mengobarkan perang di kepulauan Falkland, dan menghancurkan serikat buruh. Kita tahu, penghancuran serikat buruh di Inggris disertai dengan represi brutal dan sangat kejam.
Kedua, proses penerapan neoliberalisme terhadap negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia, adalah melalui cara-cara licik: jebakan utang. John Perkins, penulis buku Confessions of An Economic Hit Man, menceritakan bagaimana utang untuk mencekik leher negara penerima pinjaman. Setelah negara penerima pinjaman ini bertekuk lutut, negara kreditur pun dengan leluasa memaksakan kebijakan yang dikehendakinya.
Kita juga masih ingat, pada tahun 1997, ketika Indonesia terperosok dalam krisis ekonomi, IMF datang menawarkan pinjaman. Dalam waktu singkat Indonesia masuk dalam jebakan IMF. Sejak itu, Indonesia pun dipaksa menjalankan resep-resep neoliberal yang dikehendaki IMF. Dan, kita tahu, semua kebijakan IMF itu membawa malapetaka bagi rakyat Indonesia.
Ketiga, neoliberalisme ditandai oleh supremasi pasar dan korporasi terhadap negara dan, dengan demikian, rakyat. Dalam kondisi seperti ini, negara hanya difungsikan sebagai alat untuk memfasilitasi proses akumulasi keuntungan bagi segelitir elit/korporasi. Sedangkan suara rakyat, yang biasanya diminta setiap lima tahun sekali, tak lebih sebagai legitimator untuk berjalannya administrasi neoliberal.
Ini juga terjadi dalam kasus Indonesia. Sejak neoliberalisme dipraktekkan, partisipasi rakyat dalam politik merosot tajam. Bahkan, neoliberalisme sangat aktif mendepolitisasi massa-rakyat. Akibatnya, sekalipun ada proses pemilu reguler setiap lima tahun, tetapi proses pengambilan keputusan secara real telah berpusat di tangan segelintir elit.
Hasil survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menemukan, hanya 12,8 persen rakyat Indonesia yang mengaku bisa mempengaruhi pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan. Sebaliknya, mayoritas rakyat merasa sudah dikesampingkan dalam proses pengambilan kebijakan. Belum lagi, upaya rakyat untuk mempengaruhi kebijakan, misalkan dengan aksi protes, seringkali berhadapan dengan represi brutal.
Keempat, ketergantungan rezim nasional terhadap kekuatan kapital global telah mendorong transfer kekuasaan politik ke tangan kapital finansial. Akibatnya, para bankir, spekulan, investor, dan lembaga keuangan semakin punya kekusaan yang tak terbatas. Lembaga keuangan dan perdagangan internasional, seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO, telah mengambil peran dominan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi dan politik di Indonesia. Bahkan, kekuasaan mereka bisa melampaui kekuasaan DPR. Faktanya: hampir semua proses penyusunan UU di DPR tidak terlepas dari arahan lembaga-lembaga tersebut. Politisi PDIP Eva Sundari pernah mengungkapkan keberadaan 76 UU yang draftnya disusun oleh pihak asing. Artinya, proses penyusunan kebijakan di Indonesia, termasuk UU, tidak lagi mengacu pada konstitusi (UUD 1945) dan kehendak rakyat.
Dengan demikian, ada korelasi antara meningkatnya ketimpangan ekonomi dan semakin tersingkirnya rakyat dalam proses menentukan arah kebijakan pembangunan sebuah negara. Dan, di bawah sistem neoliberalisme, partisipasi rakyat dalam politik makin terdegradasi.













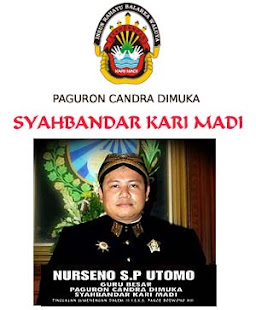









0 comments:
Posting Komentar